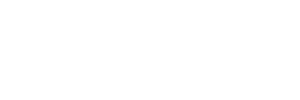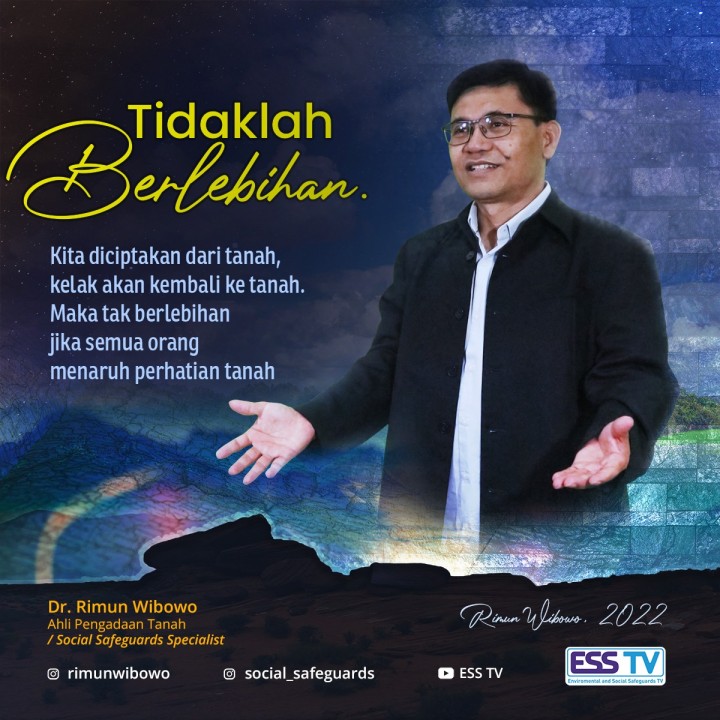
Tanah dan Keadilan: Menggagas Ganti Rugi yang Manusiawi dalam Pengadaan
Tanah sebagai bagian dari hidup
Kita semua berasal dari tanah, dan suatu saat kelak akan kembali ke tanah. Ungkapan ini lebih dari sekadar pepatah. Ia mencerminkan betapa eratnya hubungan manusia dengan tanah: tempat kita mendirikan rumah, menanam penghidupan, hingga menguburkan leluhur. Tidak heran bila setiap orang memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah yang dimiliki atau dikuasai.
Ketika tanah itu terusik atau hendak diambil alih, reaksi yang muncul hampir selalu berupa pembelaan. Bukan semata karena nilai ekonomi, melainkan juga karena tanah menyimpan makna emosional, sosial, bahkan spiritual.
Kewajiban negara dan problem keadilan
Dalam kerangka pembangunan, negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan tanah demi kepentingan umum. Jalan tol, waduk, hingga proyek energi tidak mungkin terwujud tanpa pengadaan lahan. Namun kewenangan itu tidak datang tanpa batas. Konstitusi mewajibkan pemerintah memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada warga yang tanahnya terdampak.
Persoalannya, makna “layak dan adil” sering direduksi menjadi soal angka. Tanah dinilai berdasarkan harga pasar, dihitung oleh appraisal, lalu dibayar. Di atas kertas, semua prosedur terpenuhi. Tetapi di lapangan, warga sering merasa kehilangan lebih dari sekadar sebidang tanah:
-
Mereka kehilangan sumber penghidupan.
-
Mereka tercerabut dari komunitas sosial.
-
Mereka khawatir ikatan leluhur dan identitas budaya ikut terputus.
Di sinilah konflik pengadaan tanah biasanya lahir. Pemerintah merasa sudah adil karena membayar sesuai aturan. Warga merasa sebaliknya: ganti rugi tidak pernah sebanding dengan kehilangan yang mereka alami.
Dari uang menuju keberlanjutan
Jika pembangunan ingin berjalan tanpa meninggalkan luka sosial, ganti rugi tidak boleh berhenti pada nominal. Pemerintah perlu memikirkan model yang lebih manusiawi, misalnya:
-
Pemulihan penghidupan (livelihood restoration): memastikan warga tetap bisa mencari nafkah setelah tanah mereka hilang.
-
Berbagi manfaat proyek (community benefit sharing): warga ikut merasakan manfaat langsung, misalnya melalui infrastruktur sosial, saham, atau program pemberdayaan.
-
Pengakuan nilai budaya: menghormati situs leluhur, memberi ruang ritual, atau mekanisme simbolik lain yang relevan dengan keyakinan masyarakat.
Pendekatan ini bukan hanya etis, tetapi juga strategis. Konflik sosial yang berlarut justru membuat proyek mandek, biaya membengkak, dan kepercayaan publik merosot.
Membangun tanpa mengorbankan
Tanah adalah pangkal kehidupan, bukan sekadar aset ekonomi. Karena itu, pengadaan tanah untuk pembangunan tidak boleh dilakukan secara kaku dan administratif belaka. Pemerintah memang berhak mengambil tanah untuk kepentingan umum, tetapi hak itu hanya sah bila dijalankan dengan kewajiban menghadirkan keadilan substantif.
Keadilan bukan hanya soal “ganti rugi sesuai aturan”, melainkan pengakuan bahwa tanah menyimpan nilai sosial, budaya, dan spiritual yang tak ternilai. Hanya dengan cara ini pembangunan bisa berjalan beriringan dengan kepercayaan rakyat, tanpa meninggalkan luka yang sulit disembuhkan.